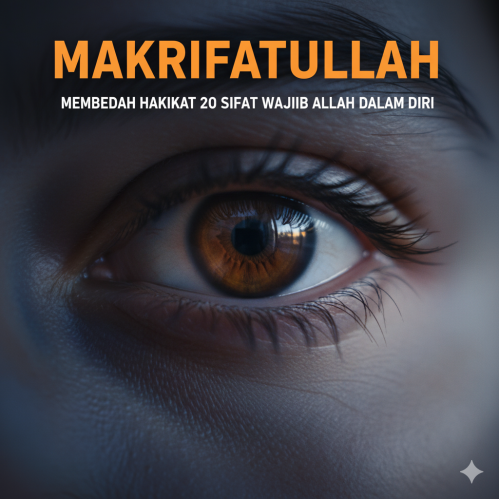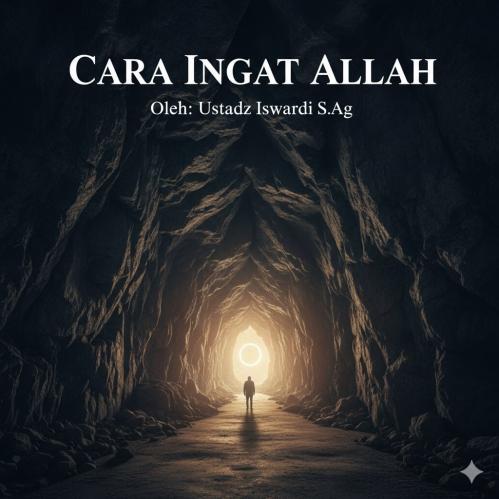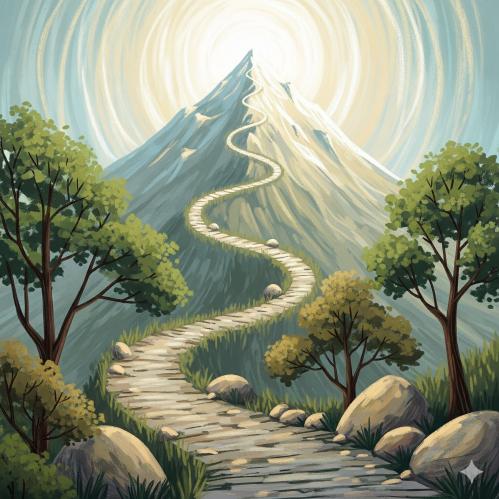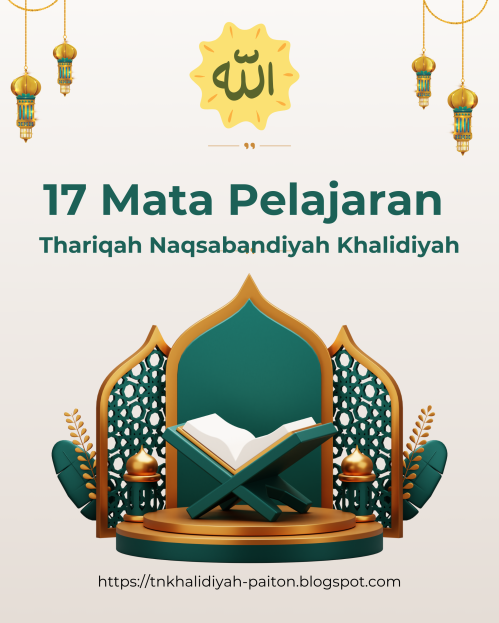Member Login

Jalan menuju Allah : Syari'at, Thariqat, Hakikat dan Ma'rifat
Secara bahasa ketiga istilah ini (Syariat, tariqat, hakikat ) tersebut memiliki arti yang sama yaitu jalan.
Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang menjadi mahaguru ulama-ulama di Nusantara, memberikan analogi dalam Kitab Maraqi Al-Ubudiyyah bi Syarhi Bidayah Al-Hidayah sebagai berikut :
“Sebagian ulama memberikan permisalan bahwa syariah itu ibarat perahu, thoriqah ibarat lautan, dan hakikat Ibarat mutiara. Seseorang tidak akan mendapat mutiara kecuali dari lautan dan tidak bisa mengarungi lautan tanpa perahu”.
“Sebagian ulama memberikan permisalan dari ketiganya ibarat kelapa. Syariat itu ibarat kulit luarnya. Thoriqah itu ibarat daging buah kelapa. Hakikat itu ibarat minyak yang ada dalam daging buah”
Analogi tersebut juga ada dalam Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhaju Al-Ashfiya’ Karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syatho Al-Dimyati. Perahu itu sebagai sebab untuk mencapai tujuan, dan penyelamat dari tenggelam. Lautan itu tempat tujuan (mutiara) tersebut berada. Sehingga, mutiara enggak akan bisa ditemukan kecuali di dasar lautan dan enggak akan bisa mengarungi lautan tanpa perahu.
Menurut Syeikh Ahmad bin Ajibah dalam Mi’raju At-Tasyawwuf Ila Haqaiq At-Tasawwuf, syariat adalah pembebanan pada aspek-aspek dzahir. Tarekat adalah memperbaiki aspek-aspek batin untuk mempersiapkan terbitnya cahaya- cahaya hakikat. Hakikat adalah penyaksian (musyahadah) terhadap Al-Haq di dalam manifestasi (tajalli-tajalli) yang dzahir. Syariat itu untuk memperbaiki aspek dzahir. Tarekat itu untuk memperbaiki aspek batin. Hakikat itu menghiasi ruh (sarair).
1. SYARIAT
Syariat jika ditinjau secara bahasa berasal dari turunan kata شَرَعَ – يَشْرَعُ – شَرْعًا yang berarti membuat peraturan atau undang-undang.
Iyad Hilal dalam bukunya “Studi Tentang Ushul Fiqih”
memberi definisi bahwa Menurut pengertian bahasa, istilah syariat berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, dimana manusia dapat memuaskan dahaganya. Dengan demikian pengertian bahasa ini-syariat atau hukum Islam ini dijadikan sebagai pedoman sumber pedoman.
Dalam dunia tasawuf syariat adalah syarat mutlak bagi salik (penempuh jalan ruhani) menuju Allah. Tanpa adanya syariat maka batallah apa yang diusahakannya. Berkaitan dengan ini pemakalah mengambil pandangan Sirhindi mengenai syariat sebagai landasan tasawuf yang diambil dari buku “Sufism and Shari‘ah” yang ditulis oleh Muhammad Abdul Haq Ansari.
Sirhindi menggunakan dua makna berkaitan dengan istilah syariat, yaitu makna umum yang biasa digunakan oleh para ulama yang berkaitan dengan penyembahan dan ibadah-ibadah, moral dan kemasyarakatan, ekonomi dan kepemerintahan yang sudah dijelakan oleh para ulama. Makna kedua, adalah pemaknaan yang lebih luas, yaitu, apapun yang telah Allah perintahkan baik secara langsung (wahyu) maupun melalui nabi-Nya itulah yang disebut syariat.
Dengan pemaknaan tersebut maka syariat meliputi segala lini kehidupan. Syariat bukan hanya tentang shalat, zakat, puasa dan haji semata. Tapi lebih dari itu, syariat adalah aturan kehidupan yang mengantarkan manusia menuju realitas sejati. Syariat merupakan titik tolak keberangkatan dalam perjalanan ruhani manusia. Maka bagi orang yang ingin menempuh jalan sufi, mau tidak mau ia harus memperkuat syariatnya terlebih dahulu.
Ada sebagian orang berpendapat bahwa syariat itu hanyalah titik tolak menuju makrifat dan ketika sudah mencapai hakikat maka ia terlepas dari syariat, karena menurut mereka syariat itu hanya untuk orang awam. Pandangan yang seperti ini ditolak oleh Sirhindi. Ia berpendapat bahwa antara syariat dan hakikat itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah bentuk lahir dari hakikat dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Mereka yang menyatakan bahwa syariat berlaku untuk orang awam dan tidak bagi orang khusus, maka mereka telah melakukan bidah tersembunyi dan kemurtadan.
‘Mereka yang lebih maju (dalam sufisme) membutuhkan ibadah sepuluh kali lipat ketimbang pemula; untuk perkembangan mereka tergantung pada pengabdian dan perolehan mereka dikondisikan atas keistikomahannya menaati syariat.’
Adapun ketika seseorang mencapai kasyf (penyingkapan), maka kasyf itu tidak bisa disejajarkan dengan wahyu. Dalam arti kasyf tidak menghasilkan produk syariat yang baru. Kasyf bisa membantu menguatkan keyakinan kebenaran syariat. Juga, dengan kasyf seseorang bisa mengetahui mengenai sunnah Nabi yang dianggap lemah oleh ulama padahal sangat dianjurkan oleh Nabi atau sebaliknya. Tapi tidak sedikitpun perolehan kasyf ini memproduksi syariat baru. The kashf of sufi may be right or it may be wrong.
Jika ide-ide yang didapat dari kasyf itu kontradiksi dengan syariat, maka ia dalam keadaan mabuk dan dianggap tidak benar.
Berbeda dengan Sirhindi, menurut al-Ghazali wahyu yang didalamnya memuat syariat itu penuh dengan bahasa simbolik dan metafora, penafsiran terbaik adalah melalui kasyf, begitu juga dengan pandangan Ibn Arabi. Sehingga kasyf bisa disejajarkan dengan wahyu. Menurut hemat pemakalah, walaupun kasyf itu bisa menguak makna-makna dari wahyu, namun kedudukan kasyf hanyalah sebagai penguat apa yang ada dalam wahyu.
2. TAREKAT
Tarekat secara bahasa berasal dari kata الطَّريْقُ jamaknya طُرُق dan اَطْرُق yang bermakna jalan, lorong atau gang. Kata tersebut diturunkan menjadi الطَّريْقَةُ yang bermakna jalan atau metode. Istilah tarekat ini menunjuk pada metode penyucian jiwa yang landasannya diambil dari hukum-hukum syariat. Semua muslim wajib menerapkan syariat, namun ada sebagian muslim yang hanya berfokus pada kewajiban-kewajiban ibadah dan ada sebagian lagi yang selain fokus pada kewajiban-kewajiban ibadah juga memperhatikan adab, akhlak, dan sisi batin dari syariat itu, yang sebetulnya semua itu sudah dijelaskan dalam syariat.
Pada tataran syariat, kesadaran tentang kepemilikan pribadi begitu dominan, sehingga perlu adanya aturan untuk menata kehidupan bermasyarakat dalam keteraturan dan menghargai hak-hak pribadi, milikmu adalah milikmu dan milikku adalah milikku. Sedangkan pada tataran tarekat kesadaran tentang milik pribadi mulai luntur dan sikap mendahulukan orang lain lebih dominan, milikmu adalah milikmu dan milikku juga milikmu. Dan pada tingkatan makrifat kepemilikan hanya milik Allah.
Dalam pandangan Sirhindi, tarekat adalah bagian dari syariat karena syariat punya tiga bagian, yaitu, pengetahun, tindakan, dan niat yang murni (ikhlas). Setiap salik harus mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh syariat baik ranah ibadah mahdah maupun muamalah. Ketika ia sudah mengetahui, maka ia wajib melakukannya dengan ikhlas, yaitu semata-mata perbuatan itu ditujukan hanya untuk Allah. Inilah aspek batin syariat. Inti tauhid adalah ikhlas, dan untuk mempraktekan ikhlas tidaklah mudah. Hal itu disebabkan karena manusia cenderung memenuhi tuntutan pribadinya ketimbang memenuhi apa yang sudah Allah perintahkan dan Allah larang. Selain itu manusia mudah terjebak dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka diperlukan metode atau latihan-latihan untuk memantapkan ikhlas dalam setiap tindakannya (mukhlis), sehingga ikhlas itu menjadi bagian dari dirinya (mukhlas), metode itulah yang disebut tarekat.
Tarekat memberikan tahapan-tahapan yang lebih rinci dalam mendaki tangga kesempurnaan tauhid. Tapi secara umum tahap pertama yang harus dilalui adalah tahapan taubat, yaitu berkomitmen untuk kembali kepada-Nya dengan melakukan apapun yang Dia syariatkan dan memurnikan tujuan dari tujuan-tujuan selain-Nya yang diakhiri dengan tahapan makrifat, ada juga yang mengatakan tahap mahabbah. Antara tahap taubat dan tahap akhir ada banyakan tahapan yang harus dilalui, namun intinya semua itu berawal dari ikhlas dan berakhir pada sikap rida sebagai buah pencapaian kesempurnaan tauhid.
Secara umum ada tiga proses dalam tarekat untuk bisa sampai pada hakikat, yaitu mujahadah, riyadhah, dan muhasabah. Mujahadah artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, berupaya secara gigih dan berusaha dengan giat dan keras melawan hawa nafsu dan berkonfrontasi dengan syetan, agar hubungan vertikal, horizontal, dan diagonal tidak terganggu.
Yang kedua adalah riyadhah. Riyadhah (Olah Ruhani) bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan tugas dan kewajiban kita sehari-hari, serta tidak harus menghilangkan pemenuhan hak-hak kita terhadap diri, keluarga, dan masyarakat sosial.
Inti dari riyadhah adalah konsisten dan istikomah. Riyadhah bisa dilakukan dengan zikir, memperbanyak ibadah dan doa. Proses yang ketiga adalah muahasabah. Yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah adalah merenungkan dan menetapkan dengan membedakan apa yang tidak disenangi oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan apa yang disukai-Nya.
Adapun tarekat dalam bentuk institusi baru muncul pada abad 11. Awalnya merupakan gerakan bersifat privat yang dilakukan oleh orang-orang yang sepaham pada awal-awal masa Islam, akhirnya tumbuh menjadi suatu kekuatan sosial utama yang menembus sebagaian besar masyarakat Muslim.
Kemunculan tarekat ini dikarenakan adanya hubungan antara mursyid-murid. Mursyid sebagai pembimbing yang mengarahkan murid (yang dibimbing) menuju hakikat sejati. Biasanya tarekat yang berkembang sekarang dinisbahkan pada mursyid tertentu yang dianggap punya metode tersendiri yang khas, seperti Suhrawardiyah diambil dari nama Abu Hafs as-Suhrawardi, Syazilliyah diambil dari Abul Hasan al-Syazili. Para pendiri tersebtu adalah para mursyid yang telah membuat kodifikasi serta melembagakan pengajaran dan praktik-praktik tarekatnya yang khas, meskipun pada banyak kasus reputasi mereka sebagai wali jauh melebihi lingkaran kelompoknya.
3. HAKIKAT
Dalam Kamus Ilmu Tasawuf, dikatakan bahwa Kata Hakikat (Haqiqah) seakar dengan kata al-Haqq, reality, absolute, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran atau kenyataan. Makna hakikat dalam konteks tasawuf menunjukkan kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi manusia dan teologis. Adapun dalam tingkatan perjalanan spiritual, Hakikat merupakan unsur ketiga setelah syari’at yang merupakan kenyataan eksoteris dan thariqat (jalan) sebagai tahapan esoterisme, sementara hakikat adalah tahapan ketiga yang merupakan kebenaran yang esensial. Hakikat juga disebut Lubb yang berarti dalam atau sari pati, mungkin juga dapat diartikan sebagai inti atau esensi.
Secara terminologis, kamus ilmu Tasawuf menyebutkan bahwa Hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syari’at itu, sehingga hakikat adalah aspek yang paling penting dalam setiap amal, inti, dan rahasia dari syari’at yang merupakan tujuan perjalanan salik.
Hakikat juga dapat diartikan sebagai sebuah afirmasi akan eksistensi wujud baik yang diperoleh melalui penyingkapam dan penglihatan langsung pada substansinya, atau juga dengan mengalami kondisi-kondisi spiritual, atau mengafirmasi akan ketunggalan Tuhan.
Tokoh sufi lainnya, Ahmad Sirhindi, mendefinisikan hakikat sebagai persepsi akan realitas dalam pengalaman mistik. Sementara penafsiran Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara mengenai Hakikat adalah dari sudut pandang dimana banyak para sufi menyebut diri mereka ‘ahl-haqiqah’ dalam pengertian sebagai pencerminan obsesi mereka terhadap ‘kebenaran yang hakiki’ (kebenaran yang esensial). Contoh salah satu sufi dalam kasus ini adalah al-Hallaj (w. 922) yang mengungkapkan kalimat ‘ana al-Haqq’ (Aku adalah Tuhan). Obsesi terhadap hakikat ini tercermin dalam penafsiran mereka terhadap formula ‘la ilaha illa Allah’ yang mereka artikan ‘tidak ada realitas yang sejati kecuali Allah’. Bagi mereka Tuhanlah satu-satunya yang hakiki, dalam arti yang betul-betul ada, ada yang absolut, sementara yang selainNya keberadaanya bersifat tidak hakiki atau nisbi, dalam arti keberadaannya tergantung kepada kemurahan Tuhan.
Jika kita ingin menjelaskannya melalui analogi, maka hubungan antara Tuhan dan yang selainNya ini ibarat matahari. Dia lah yang yang memberikan cahaya kepada kegelapan dunia, dan menyebabkan terangnya objek-objek yang tersembunyi dalam kegelapan tersebut. Dia jualah yang merupakan pemberi wujud.Pernyataan ‘la ilaha illa Allah’ ditafsirkan para sufi sebagai penafian terhadap eksistensi dari yang selain-Nya, termasuk eksistensi dirinya sebagai realitas. Hal ini tampak jelas pada konsep ‘fana’ , atau ‘fana al-fana’ yang merupakan ekspresi sufi akan penafian dirinya. Sedangkan konsep baqa adalah afirmasi terhadap satu-satunya realitas sejati, yaitu Allah. Fana’ dan baqa’ ini dipandang sebagai ‘stasion’ (maqam) terakhir yang dapat dicapai para sufi. Inilah maqam yang paling diupayakan untuk dicapai oleh para sufi melalui metode tazkiyatun nafs, dengan menyingkirkan ego mereka yang dianggap sebagai kendala dari perjalanan spiritual mereka menuju Tuhan. Dengan begitu, ibadah mereka terbersihkan dari segala unsur syirik sebagai syarat diperkenankannya masuk kehadirat Tuhan. Rumi pernah berkata, “Lobang jarum bukanlah untuk dua ujung benang.”
4. MAKRIFAT
Dalam kamus ilmu tasawuf dikatakan bahwa Makrifat berasal dari kata ‘arafa, yu’rifu, ‘irfan, ma’arifah, yang artinya adalah pengetahuan, pegalaman, atau pengetahuan ilahi. Secara terminologis dalam kamus ilmu tasawuf, Makrifat diartikan sebagai ilmu yang tidak menerima keraguan atau pengetahuan. Selain itu, Makrifat dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya.
Sedangkan menurut para sufi, makrifat merupakan bagian dari tritunggal bersama dengan makhafah (cemas terhadap Tuhan) dan mahabbah (cinta).Ketiganya ini merupakan sikap seseorang perambah jalan spiritual (thariqat). Makrifat yang dimaksud di sini adalah pengetahuan sejati.
Gagasan mengenai adanya konsep makrifat dimunculkan pertama kali oleh Dzu al-Nun al-Misri. Menurutnya makrifat ada 3 macam :
1. Pertama, makrifat kalangan orang awam (orang banyak pada umumnya), tauhid melalui syahadat.
2. Kedua, makrifat kalangan ulama dan para filsuf yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam ini, mereka mengetahui Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran.
3. Ketiga, makrifat kalangan para wali dan orang-orang suci; mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Inilah makrifat hakiki dan tertinggi dalam tasawuf.